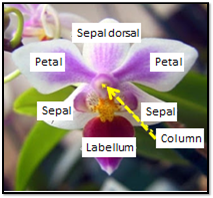MENGENAL “
KARRIKINS” ZAT PENGATUR TUMBUH BERBASIS
ASAP
OLEH IMAS AISYAH
SP., M.Si
(FUNGSIONAL UMUM
P4TK PERTANIAN CIANJUR)
Zat
pengatur tumbuh adalah senyawa organik yang diproduksi secara alami di dalam
tumbuhan, dan pada konsentrasi rendah memiliki
peran penting dalam mengontrol proses biologi dalam jaringan tanaman. Zat pengatur tumbuh juga dikenal dengan
sebutan fitohormon, yang berperan sebagai pembawa pesan kimia yang mengontrol
siklus hidup dan kegiatan fisiologis seperti perkecambahan, regulasi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti pembentukan batang, daun, tunas,
buah, pengembangan dan pemtangan buah, perkembangan akar, pemanjangan akar
rambut dan pembentukan akar lateral, dan lain-lain
(Davies, 1995; Gaba, 2005). Ada 5 jenis ZPT yang diproduksi secara alami oleh
tumbuhan yang sudah dikenal khalayak yaitu: auksin, sitokinin, etilen,
giberelin, dan asam absisat (ABA). Selain
itu, ada juga fitohormon dari kelas butenolide yang dilepaskan oleh akar
tanaman sebagai adaptasi tanaman pada saat tanaman mengalami stress dari
lingkungan, salah satunya adalah Strigolactone (Koltai &
Kapulnik 2011).
Strigolactones adalah kelompok sesquiterpen
lakton yaitu sejenis metabolit sekunder yang dilepaskan
oleh akar tanaman pada saat kondisi stres biotik dan abiotik. Sesquiterpen lakton yang dilepaskan oleh akar tanaman dari kelompok Asteraceae
dilaporkan memiliki efek biologis yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman (Chadwick et al.
2013). Strigolactone sendiri adalah
fitohormon yang memiliki efek positif pada pengembangan akar, yaitu terhadap pemanjangan akar rambut dan pembentukan akar lateral (Koltai 2011). Strigolactone juga diduga menjadi
regulator kunci dari respon adaptif tanaman terhadap fosfat rendah dengan memodulasi keseimbangan antara auksin dan
etilen signaling yang bertanggung jawab atas perkembangan akar (Koltai 2013). Dalam tulisan
ini penulis akan menginformasikan satu jenis ZPT yang mungkin belum dikenal oleh
khalayak secara luas, baik namanya, peran, dan mekanisme kerjanya dalam
mengatur pertumbuhan tanaman.
Ada yang berpendapat karrikins bukanlah fitohormon kerena
tidak dproduksi oleh tumbuhan, pendapat ini ada benarnya, karena karrikins hanya ditemukan di dalam asap hasil
pembakaran kayu. Namun, senyawa karrikins (3-methyl-2H-furo[2,3-c]pyran-2-one) memiliki
kemiripan struktur dan kemiripan efek fisiologis dengan fitohormon tanaman “strigolactone”, dari kelas butenolide, sehingga karrikin kemudian
dimasukkan ke dalam zat pengatur tumbuh baru dari kelas butenolide yang berasal dari asap (Chiwocha et al. 2009).
Senyawa dalam asap (pada teknik
pengasapan langsung) diyakini selain dapat menurunkan kadar air benih hasil panen, juga dapat memperpanjang masa
simpan benih atau mengawetkan benih, meminimalkan kerusakan benih
dari serangan hama atau patogen
benih, dan dapat meningkatkan
perkecambahan benih dan vigor bibit (Paasonen et al. 2003). Peran asap dalam memecahkan dormansi benih,
merangsang perkecambahan beih dan pertumbuhan bibit telah dipelajari sejak
tahun 1990, dan baru pada tahun 2004 senyawa aktif di dalam asap yang berperan
dalam memecahkan dormansi benih, merangsang perkecambahan benih dan pertumbuhan
bibit ditemukan, dan senyawa tersebut adalah “karrikins” (Flematti et al. 2004). Menurut Flematti et al. (2011), senyawa karrikins berasal dari penguraian termal
(pirolisis) karbohidrat seperti selulosa.
Karrikins dilaporkan dapat meningkatkan
pertumbuhan bibit dan vigor bibit pada banyak spesies yaitu sekitar 1200
spesies lebih dari 80 famili (Dixon et al.
2009). Karrikins
memiliki rumus kimia C8H6O3,
dan
strukturnya dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar
1. Struktur karrikins
Menurut Kepczynski
&Van Stade (2012) dan Johnson & Ecker (1998), karrikins bekerja
sebagai sinyal positif untuk pembentukan ACC (Aminocyclopropane-1-carboxylate) yang menjadi
prekursor dalam pembentukan etilen endogen dalam tanaman. Mekanisme
biosintesis etilen dari metionine dapat dilihar pada Gambar 2. Biosintesis etilen dari metionin diawali dengan konversi metionin menjadi
SAM (S-Adenosylmethionine) yang diaktivasi oleh enzim SAM synthase,
selanjutnya konversi SAM menjadi ACC(Aminocyclopropane-1-carboxylate)
diaktivasi oleh ACC synthase dan konversi ACC menjadi etilen diaktivasi oleh
ACC oxidase (Pratt & Goeschl 1969).
Gambar 2. Mekanisme
biosintesis etilen (Pratt&Goeschl 1969)
Keterangan: SAM= S-Adenosylmethionine;
ACC=Aminocyclopropane-1-carboxylate
Sebagaimana
fitohormon berperan sebagai sinyal yang dapat mengaktifkan
gen yang potensial, senyawa karrikins juga berperan sebagai sinyal
biologis/prekursor yang dapat mengaktifkan transkripsi keluarga gen IAA (Indole-3-Acetic Acid ), seperti
IAA1, IAA5 dan IAA6, yang berperan dalam biosintesis auksin (Waters
et al. 2014). Mekanisme karrikins dalam
menginduksi gen auksin (IAA) digambarkan dalam
Gambar 3.
Dari
Gambar 3 dijelaskan bahwa senyawa karrikin juga berperan sebagai sinyal
biologis/prekursor yang dapat mengaktifkan transkripsi keluarga gen IAA (Indole-3-Acetic Acid), seperti IAA1,
IAA5 dan IAA6, yang
berperan dalam biosintesis auksin (Waters et al. 2014). Mekanisme karrikins dalam
menginduksi gen auksin (IAA) digambarkan dalam
Gambar 5. Dari Gambar 5 dijelaskan bahwa sinyal karrikin dapat
dikenali oleh protein reseptor yaitu KAI2 (Karrikin Insensitive 2), KAI2 adalah protein α/β-hydrolase yang memiliki aktivitas
mengkatalisis hidrolisis atom karbonil dari cincin butenolide dari karrikin,
pembukaan cincin butenolide ini akan mempercepat proses tranduksi sinyal
karrikin pada tanaman. KAI2
ini akan berikatan dengan komplek SCF-MAX2 (F-Box), dan kompleks KAI2-SCF-MAX2
(F-Box), akan dikenali dan diikat oleh represor (SMAX1), SMAX1 adalah protein
penekan MAX2 (F-Box), sehingga transkripsi gen-gen target tidak
terjadi. Supaya transkripsi gen-gen
target terjadi, maka SMAX1 ini harus dihancurkan. SMAX1 ini dihancurkan oleh protein ubiquitin
(Ub) yaitu SCF. SCF mempunyai peran yang
sama dengan domain APC (Anaphase-Promoting-Complex),
yang dapat mengenali protein target secara spesifik yang akan
dihancurkannya. Setelah protein target
(SMAX1) hancur, maka kompleks KAI2-SCF-MAX2 (F-Box), ini
kemudian akan aktif bekerja untuk mentrankripsi gen-gen target, salah satunya
gen IAA1 dan IAA5, IAA6 yang berperan dalam biosintesis auksin (Indole-3-Acetic Acid), kehadiran auksin
ini akan menginduksi gen GA3ox yang berperan dalam biosintesis giberelin, dan
giberelin ini bekerja mengatur petumbuhan tanaman, termasuk proses
perkecambahan biji, pengembangan bibit, daun dan bunga. Karrikins juga dilaporkan dapat menginduksi
transkripsi gen GA3ox1 dan GA3ox2 yang berperan dalam biosintesis giberelin (GA)
(Nelson et al. 2009).
Gambar 3.
Mekanisme karrikin dalam menginduksi gen IAA
(Waters et al. 2014)
Karrikins juga diduga menjadi sinyal yang menengahi pengaturan cross-talk antar
hormonal seluler, sesuai dengan
pendapat Johnson
& Ecker (1998) dan Chang
& Stadler (2001) melaporkan bahwa karrikin berperan sebagai sinyal
yang memicu pembentukan etilen endogen dalam tanaman, dan sinyal
etilen dapat memicu pembentukan hormon auksin, selanjutnya sinyal auksin dapat
mengaktifkan hormon giberelin, dan giberelin tersebut kemudian akan meregulasi pertumbuhan tanaman. Interaksi antar hormon etilen, auksin dan gibberelin dalam
meregulasi pertumbuhan tanaman dijelaskan dalam
Gambar 4.
Gambar 4. Skema
integrasi hormon etilen, auksin dan
giberelin
(GA) dalam meregulasi pertumbuhan tanaman
(Archard et a.l 2003)
Dari Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa interaksi antar hormon etilen, auksin dan gibberelin
dalam meregulasi pertumbuhan tanaman. Menurut Archard et al. (2003), sinyal etilen dikenali dan diikat oleh
protein reseptor, salah satunya oleh ETR,
pengikatan sinyal etilen oleh ETR ini akan menginaktivasi CTR1 (regulator negatif EIN2 (Ethylen Insensitive 2)), dan inaktivasi CTR1 ini akan memungkinkan EIN2 (Ethylen Insensitive 2) aktif dan
berinteraksi dengan EIN3 (Ethylen
Insensitive 3), selanjutnya EIN3 ini akan berikatan dengan ERF1 (Ethylen Responsive Factor 1), selanjutnya
kompleks EIN3-ERF1 ini menjadi faktor transkripsi yang akan pergi dan bergerak
ke daerah mRNA, yang terdapat di nukleus, kemudian akan duduk berdekatan dengan
Cis Acting Element (GCC Box) (AGCCGCC) yang terdapat di daerah promotor, dan
kondisi ini akan
memediasi transkripsi
gen-gen target termasuk gen yang mengatur biosintsis Auksin. pada saat tidak
ada auksin, hormon ABA hadir untuk menekan
giberelin dan protein DELLA yang berperan dalam menekan aktivitas giberelin akan mengikat giberelin (GA) sehingga giberelin (GA) menjadi tidak aktif. Tetapi setelah sinyal auksin hadir, hormon ABA akan ditekan dan GA akan
setengah aktif karena masih berikatan dengan protein DELLA, untuk melepaskan
ikatan protein DELLA, GA akan
berikatan dengan reseptor protein GID1 (GA-INSENSITIVE DWARF 1)
melalui ikatan hidrogen, sehingga terbentuk ikatan kompleks GA-GIDI, selanjutnya GA-GIDI ini akan
dikenali dan diikat oleh protein SCFSLY1 (Protein SCFSLY1 ini dapat mengenali
protein target (protein DELLA) yang akan dihancurkannya secara spesifik). Kemudian kompleks GA-GID1-SCFSLY1 ini akan mengenali dan mengikat protein DELLA, dan kemudian menghancurkan
protein DELLA, jika protein DELLA terdegradasi, maka GA menjadi
aktif dan jika sudah aktif GA akan meregulasi berbagai aspek dari siklus hidup
tanaman dan respon pertumbuhan lainnya.
Semoga tulisan
ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Terimakasih.
DAFTAR
PUSTAKA
Archard
P, Vriezen
HW, Van Der Straeten
D, Harberd PN. 2003.
Ethylene Regulates Arabidopsis Development via the Modulation of DELLA
Protein Growth Repressor Function. Plant Cell. 15(12): 2816-2825.
Chadwick M, Trewin H, Gawthrop F, Wagstaff
C. 2013.
Sesquiterpenoids
Lactones: Benefits to Plants and People.
Int J Mol Sci. 14(6):
12780–12805.
Chang C and Stadler R. 2001. Ethylen hormon receptor action in
Arabidopsis. Bioessay. 23(7): 619-627.
Chiwocha SDS,
Dixon WK, Flematti RG,
Ghisalberti LE, Merritt JD,
Nelson CD, Riseborough MJ, Smith MS, Stevens CJ. 2009. Karrikins: a new family of plant growth
regulators in smoke. Plant Sci.
177: 252–256. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2009.06.007
Davies, P.J. 1995. The plant
hormone their nature, occurence and function. In Davies (ed.) Plant Hormone and
Their Role in Plant Growth Development. Dordrecht Martinus Nijhoff Publisher
Dixon KW,
Merrtit DJ, Flematti GR, Ghisalberti EL. 2009.
Karrikinolide a phytoreactive compound derived from smoke with
application in horticulture, ecological restoation and agriculture. Acta
Horti. 813: 155-170.
Flematti RG,
Ghisalberti LE, Dixon WK, Trengove DR.
2004. A compound from smoke that promotes seed germination. Science.
305: 977
Flematti RG, Merritt
JD, Piggott JM, Trengove DR, Smith MS, Dixon WK, Ghisalberti LE. 2011. Burning vegetation produces cyanohydrins that
liberate cyanide and promote seed germination.
Nat. Commun. 2: 360.
Gaba, V.P. 2005. Plant Growth Regulator. In R.N. Trigiano
and D.J. Gray (eds.) Plant Tissue Culture and Development. CRC Press. London.
p. 87-100
Johnson PR, Ecker JR. 1998. The ethylen gas signal transduction pathway:
a molecular perspective. Annu Rev. Genet. 32: 227-254.
Kepczynski, J., Van Staden, J.
2012. Interaction of karrikinolide and
ethylen in controlling germination of dormant Avea fatua L. Caryopsis. Plant Growth Regul. 67:185-190.
Koltai H, Kapulnik Y. 2011. Strigolactones as mediators of
plant growth responses to environmental conditions. Plant Signal Behav. 6(1):37-41
Koltai H. 2013. Strigolactones activate different hormonal pathways
for regulation of root development in response to phosphate growth
conditions. Ann Bot. 2013 Jul;112(2):409-15. Doi: 10.1093/aob/mcs21
Nelson DC, .
2009. Karrikins discovered in smoke trigger
Arabidopsis seed germination by a mechanism requiring gibberellic acid
synthesis and light. Plant Physiol 149:863–873.
Paasonen, M., Hannukkala, A., Ramo, S., Haapala, H.,
Hietaniemi, V. (2003). Smoke-a novel
application of a traditional means to improve grain quality. In: Nordic
Association of Agricultural Scientists 22nd Congress, Turku, Finland.
Pratt HK, Goeschl JD. 1969. Physiological roles of ethylen in
plants. Annual Revies of Plant Physiology. 20: 541-584
Waters TM, Scaffidi A, Sun KY,
Flematti RG, Smith MS. 2014.
The karrikin response system of Arabidopsis. The
Plant Journal. 79: 623–631. Doi: 10.1111/tpj.12430